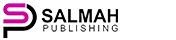Cerpen I Api Rimba I Rian Harahap

API RIMBA
Mulutnya masih mengunyah sirih. Dengan kepala yang mengangguk ke atas dan bawah. Sambil menggumam merapal mantra-mantra. Di sakunya, masih ada dua helai sirih yang masih utuh. Suaranya bertempo, kadang cepat, lambat dan beberapa waktu senyap. Nafasnya mendengus, seperti lelaki yang dikejar singa dalam rimba raya. Matanya membelalak, lalu sayu, ikut senada dengan tempo. Tubuhnya penuh peluh, bergetar kuat, kayu dibawahnya berantuk-antuk dengan tanah hitam yang telah mengeras.
Malam itu, Bomo Katik bertelanjang dada, berdiri lalu duduk, berulang terus. Sementara, Atan sibuk menjaga api agar tidak padam. Punggung tangannya mepet ke api, menghalau jika saja ada angin yang ingin mematikan apinya. Awang, sudah siap dengan beberapa kembang tujuh rupa, air buah limau purut, kunyit kuning satu ruas, serta sedikit minyak yang ditumbuk dengan bawang putih tunggal. Ia sangat telaten, menumbuk dengan batu penggilingan, lalu menghidangkannya dalam sebuah piring yang digenangi sedikit air. Mereka menatap Bomo Katik dengan tajam. Mulutnya pun seturut ikut meliuk serupa mulut Bomo Katik merapal mantra.
“Bagaimana? Apakah mereka masih ngotot masuk ke dalam kampung kita?”
“Nampaknya kami masih mendengar suara mesin itu Datuk!”, ucap Awang gemetar.
Suara-suara mesin itu makin meraung, beberapa tumbang ke tanah. Burung-burung mulai menjerit. Malam itu genting. Seperti di berada di atas sebuah kapal yang penumpangnya harus menyelamatkan diri, sebelum kapal tenggelam, air masuk merambat, dari buritan, dek, hingga anjungan.
Suasana pecah. Suara tangis datang dari akar-akar yang tercabut dari deru mesin. Bomo Katik secepat kilat membuka matanya. Ia berdiri, di atas batang kayu ulin.
“Kita harus berdiri disini. Mempertahankan tanah terakhir yang kita miliki!”, ucap Bomo Katik berapi-api.
Suaranya pun berlomba, diantara suara deru mesin. Ia seolah tak takut dengan apa yang akan datang ke hadapannya. Raung mesin alat berat dalam kegelapan. “Brak….!”
***
Awang berdiri di sebuah batang ulin. Matanya melihat hamparan pohon tinggi yang berjenjang ke pintu langit. Dinginnya menusuk kulit. Embun basah jatuh ke pipinya. Begitulah hutan ini dijaga dan dirawat oleh masyarakat kampung. Siapa yang menebang pohon tanpa ada pasal dan sebab akan dihukum adat.
Kayu ulin yang dipijak Awang, ditebang untuk membuat rumah baru. Ada warga yang mengikuti acara dan ritual untuk menaikkan rumah panggung baru. Kayu-kayu ulin itu telah dibacakan mantra dan siap untuk dijejerkan lalu diikat menjadi sebuah tempat berteduh baru.
Awang yang perutnya bersegi enam, lengan yang legam, uratnya keluar dengan sigap meraih kapak dari sarungnya. Ia papas, hancurkan kulit-kulit ulin yang keras. Batang ulin itu telah dihitungnya. Jarinya menunjuk mulai dari ujung mata sampai yang terhampar di depannya.
Tak lama, Atan datang dengan beberapa warga lainnya. Mereka bersarung, mata yang merah seperti matahari terbakar. Dengan langkah cepat, mulut mereka menggeram. Ada yang ingin disampaikan pada Awang. Apalagi, Awang adalah pimpinan dari kampung ini. Awang pun tak sabar, melihat wajah mereka yang memerah. Ia berdiri tak berkedip.
Atan membisu dengan muka memerah namun matanya tak lepas ke wajah Awang.
“Apa yang terjadi Atan? Aku melihat gelagat yang berbeda dari kalian.”, ucap Awang.
“Itu Wang! Itu!”
“Itu apa? Coba sampaikan dengan pelan!”
Awang tak paham dengan yang disampaikan Atan. Nafasnya yang tersengal saling berpacu dengan suara nafas warga kampung lain yang ikut. Awang melihat keringat yang mengucur deras, beberapa tampak mengangkat senjata. Ada kapak dan parang. Tandanya sudah berbeda. Kalau digenggam ke bawah maka itu pertanda digunakan untuk bekerja, tapi jika senjata itu sudah diangkat di atas kepala, seturut dan segaris dengan tubuh, pasti ada hal yang tidak beres.
“Katakan Atan! Coba kau sampaikan dengan jelas dan tenang!”, celetuknya.
Atan melepaskan pandangannya ke sekeliling. Melihat pandangan itu, warga serentak menurunkan senjatanya.
“Begini Wang, bukankah kampung kita ini sudah diberikan janji sebagai kampung adat! Tidak boleh lagi ada penebangan hutan, mengambil lubuk larangan, tapi kini mereka malah datang. Berbondong-bondong dengan suara-suara gemuruh dari mesin mereka. Ini adalah kebohongan Wang!”, sebut Atan.
“Siapa mereka? Siapa yang kau maksudkan?”
“Mereka yang pernah berjanji pada kita. Bahwa hutan ini dijaga. Mereka yang sampaikan bahwa semua yang ada di kampung ini, tanah ulayatnya dan segala hutannya adalah warisan negeri yang tak boleh diubah!”
Wajah Awang terkejut. Pasalnya, baru sebulan yang lalu pejabat itu datang dengan beberapa anggotanya. Memberikan bantuan berupa beras dan sembako lainnya. Mereka bilang ini adalah bantuan untuk warga kampung adat yang tinggal di pedalaman.
“Begini, Bapak-Bapak dan Ibu-ibu. Kedatangan kami disini adalah untuk mendata nama kepala keluarga dan jumlah anak untuk diberikan bantuan setiap tahunnya”
Saat itu memang, terjadi penolakan dari kaum perempuan kampung. Mereka tidak yakin dengan apa yang dikatakan mereka yang berpakaian rapi, memakai dasi dan berkacamata tebal itu.
“Sudahlah jangan diterima mereka. Kita tidak tahu apa maksud mereka, baik atau buruk. Biarkan kita hidup dengan kehidupan kita sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain”, celetuk seorang perempuan yang sedang menggendong bayinya.
Bayi itu menangis, seolah melihat masa depan kampung. Saat itu, orang-orang tak peduli dengan tangisan itu. Seperti tangisan bayi lainnya, yang menangis jika haus atau lapar.
Awang saat itu, berani pasang badan menjawab apa yang disampaikan perempuan itu.
“Kedatangan mereka kita terima saja. Kalau ada orang ingin membantu kenapa harus ditolak, mereka membawa makanan dan sembako untuk warga kampung ini”
Hari itu, matahari bersinar dengan terik. Angin sepoi menyambut senyum warga yang tangannya menampung beras, gula dan sembako lain. Ada guratan kebahagiaan warga kampung. Mereka percaya pada Awang, kedatangan tuan-tuan dari kota itu pasti membawa keberuntungan bagi kampung.
Semua itu menjadi paradoks ketika suara-suara gemuruh mesin alat berat itu sedang bersiap di pintu rimba. Awang tak habis pikir. Matanya memerah saga, ototnya hendak keluar dari tubuhnya. Ia menyimpan bara api. Ia juga menyembunyikan bom yang siap meledak. Sesuatu yang dari dalam tubuhnya tak pernah keluar jika tak terpaksa.
Semua kedatangan orang-orang itu telah mengubah pandangan Awang atas orang kota. Ia terduduk, bersalah. Menancapkan parangnya di batang ulin. Di sekelilingnya Atan dan warga kampung lain menunggu perintah.
“Apa yang harus kami lakukan Awang?”
Awang masih terdiam seribu bahasa. Mulutnya disumpal oleh tipu daya. Sorot matanya lesu.
“Aku telah gagal! Kita telah jatuh dalam tipu daya mereka. Kita lupa dengan apa yang kita punya”
Awang mengucapkannya dengan berkaca-kaca. Di telinganya, terdengar suara anak bayi yang menangis terus menerus, suara perempuan yang menolak, tapi di matanya tergambar pula wajah bahagia orang kampung yang senang mendapatkan makanan. Ia berada di batas pikir, merasa di pinggir jurang. Tak mampu meloncat, mesti jembatan dan tali telah dibentang. Ototnya seolah surut, menurut pada pikirnya yang melalang buana. Jatuh pada kegelisahan dan kegamangan. Kampungnya akan jadi apa, setelah digarap orang-orang itu.
“Mereka akan mengambil kampung kita. Disini akan dibangun ladang sawit, pohon kita akan ditumbang satu demi satu”, ucap Atan.
Awang seperti ditampar oleh nenek moyangnya. Ia membayangkan kemarahan dan kesedihan yang bercampur di wajah moyangnya. Ia masih bisu tak bersuara. Namun, garis wajahnya mengernyit dan berubah pilu.
Seolah ia sedang dibawa dalam dimensi yang berbeda dihukum dalam mimpinya. Mambang yang meminta pertanggungjawabannya. Menghukumnya, tubuhnya dirajam, namun warga kampung tak bisa menolong. Ia cemas, takut, lalu membalut tubuhnya dengan kedua tangan. Meringkuk seperti janin dalam rahim.
Sebaris kemudian, ia tertegun. Ada suara yang datang dari kejauhan.
“Awang! Mereka sudah bersiap masuk. Apalagi yang harus ditunggu? Bukankah kita adalah penghuni asli hutan ini?”
Suara teriakan itu datang putus-putus. Semua mata warga kampung mencari arah suara. Tampak sesosok tubuh datang dari belakang pohon-pohon. Ia muncul dengan tubuh ringkih, derap langkah gontai. Dengan ikat kepala merah serta celana dari kulit kayu.
Awang langsung meloncat. Ia turun dari kayu. Semua bayangannya akan kehancuran sirna seketika. Dicabutnya parang yang tertancap di kayu ulin. Api itu keluar membara dari tubuhnya. Ia sambut Bomo Katik yang berjalan pelan ke arahnya. Begitu pun, Atan dan warga kampung mengangkat parang dan kapaknya. Mengatur barisan, berbisik siapa yang siap untuk dikenang meninggalkan nama.
Suara mesin itu semakin dekat. Matahari tenggelam, suara rapalan mantra berbunyi di antara sembang mambang. Suara itu berebut ruang di rimba. Bayi-bayi itu kembali menangis. Menyambut malam yang berisik.
RIAN HARAHAP 33 tahun. Pecandu kopi hitam dan pendengar setia Rage Against the Machine. Ia didapuk menjadi Ketua Jaringan Teater Riau 2022-2024, Ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Kota Pekanbaru 2020-2025. Menulis sejak SMA hingga kini, karyanya berupa puisi, cerpen, esai dan naskah drama telah memenangkan berbagai lomba dan dimuat di media lokal serta nasional. Buku pertamanya novel Kelambu Waktu. Kini ia bermastautin di Pekanbaru merawat iklim menulis bersama Komunitas Jejak Langkah.